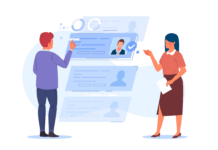Budaya ‘ Selalu Siap’ dalam Dunia Kerja Digital: Performa atau Tekanan? -Di era kerja digital, kehadiran fisik di kantor mungkin sudah tak lagi jadi keharusan. Namun, kehadiran digital tanda online, balasan cepat di chat, atau respons instan di email — kini justru menjadi standar baru. Budaya ini, yang dikenal dengan istilah “selalu siap” atau “always on”, perlahan menjadi norma dalam banyak lingkungan kerja modern.
Namun, di balik kesan profesional dan produktif, tersimpan pertanyaan penting: apakah budaya ini benar-benar mencerminkan performa yang sehat, atau justru menciptakan tekanan yang diam-diam menggerogoti kesejahteraan karyawan?
Kemajuan teknologi dan munculnya berbagai platform komunikasi kerja seperti Slack, Microsoft Teams, dan WhatsApp membuat kolaborasi jadi lebih cepat dan efisien. Ditambah lagi dengan tren remote dan hybrid working, banyak perusahaan berharap (kadang tanpa sadar) bahwa karyawannya akan selalu “tersedia”.
Ketika pesan bisa dikirim kapan saja pagi, malam, bahkan akhir pekan — muncul harapan tak tertulis: semakin cepat merespons, semakin terlihat ‘berkomitmen’. Padahal, ketersediaan terus-menerus ini sering kali bukan indikator performa, melainkan bentuk tekanan sosial yang sulit dihindari.
Budaya selalu siap tidak datang tanpa konsekuensi. Berikut beberapa dampak yang sering dirasakan para pekerja:
-
Kelelahan mental: Otak tidak pernah benar-benar istirahat. Bahkan saat tidak bekerja, pikiran tetap siaga jika tiba-tiba ada pesan masuk dari atasan atau klien.
-
Kesulitan membedakan waktu pribadi dan kerja: Akibatnya, waktu bersama keluarga, pasangan, atau diri sendiri jadi terganggu.
-
Kecemasan konstan: Banyak yang merasa bersalah jika tidak cepat merespons, bahkan saat sedang cuti atau sakit.
-
Produktivitas semu: Sekilas tampak produktif, tapi dalam jangka panjang justru menurunkan kualitas kerja dan meningkatkan risiko burnout.
Ada beberapa alasan mengapa budaya “selalu siap” masih sangat kuat:
-
Norma sosial tak tertulis: Banyak pekerja takut dianggap tidak loyal atau tidak profesional jika tidak membalas pesan dengan cepat.
-
Manajemen yang belum adaptif: Beberapa atasan masih mengukur kinerja berdasarkan kecepatan respons, bukan output kerja.
-
Kurangnya batasan jelas: Tidak semua perusahaan punya aturan tegas soal jam kerja dan komunikasi setelah jam kantor.
Budaya ‘ Selalu Siap’ dalam Dunia Kerja Digital: Performa atau Tekanan?
Untuk membangun budaya kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan, dibutuhkan perubahan mindset, baik dari manajemen maupun karyawan:
-
Fokus pada hasil, bukan kehadiran digital. Apresiasi kerja berdasarkan kualitas dan pencapaian, bukan seberapa cepat seseorang merespons chat.
-
Terapkan kebijakan “digital boundaries.” Misalnya, tidak mengirim pesan kerja di luar jam operasional kecuali darurat.
-
Gunakan tools secara bijak. Fitur seperti status “away”, “do not disturb”, atau penjadwalan email bisa membantu menciptakan ruang istirahat yang sehat.
-
Dorong budaya saling menghormati waktu pribadi. Karyawan dan atasan sama-sama perlu belajar untuk tidak menuntut respons instan sepanjang waktu.
Di era digital, kita memang bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja — tapi bukan berarti kita harus selalu bekerja.
Budaya “selalu siap” mungkin terlihat profesional di permukaan, tapi tanpa disadari bisa menciptakan tekanan psikis yang mendalam. Sudah saatnya perusahaan mulai menilai performa secara lebih bijak, dan memberi ruang bagi karyawan untuk benar-benar “off” — bukan hanya dari layar, tapi juga dari beban pikirannya.
Karena performa sejati datang dari individu yang sehat secara fisik dan mental, bukan dari mereka yang terus terhubung tanpa henti.
Baca Juga : https://blog.kitakerja.co.id/fleksibel-tapi-melelahkan-dampak-jam-kerja-tanpa-batas-di-era-remote-work/